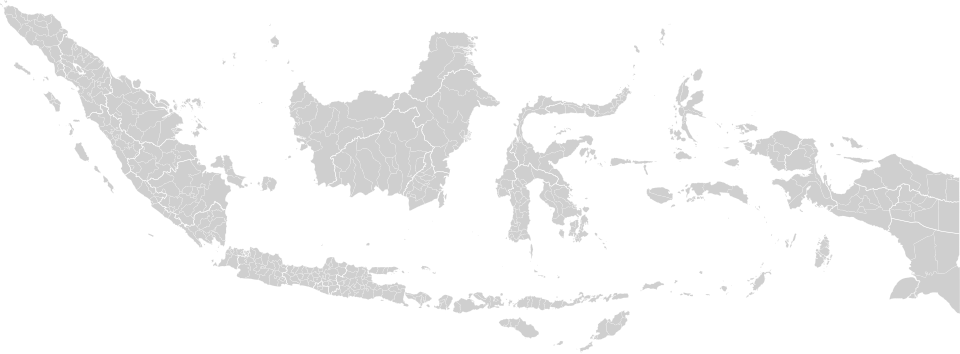Mari kita mulai dari kalimat yang paling tidak sopan bagi slogan nasionalisme yang diagung-agungkan selama ini, bahwa Indonesia hari ini gagal bukan hanya karena kurang demokrasi, namun karena terlalu lama bersembunyi di balik demokrasi prosedural yang kosong. Kita memilih, mencoblos, berdebat di televisi, tetapi struktur kekuasaan tidak pernah berubah. Demokrasi hanya menjadi ritual, sementara ketimpangan, kemiskinan serta korupsi terus direproduksi oleh sistem yang sama. Jika hasilnya selalu buruk, maka masalahnya bukan pada siapa yang berkuasa, melainkan pada cara negara ini dirancang.
Setiap kali kritik struktural diajukan, selalu ada mantra sakral yang dilemparkan sebagai senjata, NKRI harga mati. Kalimat ini terdengar heroik, tetapi secara hukum dan logika negara, ini adalah slogan kosong. Negara tidak diukur dari seberapa keras kita mempertahankan bentuknya, tetapi dari seberapa adil negara tersebut bekerja bagi warganya. NKRI yang adil layak dipertahankan. NKRI yang terus memproduksi ketimpangan layak dievaluasi secara radikal.
Selama delapan puluh tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia dijalankan dengan watak sentralistik yang ekstrem. Kekuasaan politik, fiskal, ekonomi serta simbolik terkonsentrasi di Jakarta. Pulau Jawa tumbuh menjadi pusat segalanya, sementara wilayah di luar Jawa diperlakukan sebagai penyedia sumber daya dan muara kebijakan. Ketimpangan pembangunan nasional bukan kegagalan kebijakan, melainkan hasil konsisten dari negara yang memusatkan hampir semua keputusan di satu titik.
Romo Y.B. Mangunwijaya telah lama menyebut ini sebagai arogansi pusat. Ketika pusat bermain sebagai tuan besar dan daerah dipaksa patuh, sejatinya kebencian tidak lahir karena perbedaan identitas, tetapi karena pengalaman ketidakadilan yang terus menerus. Dalam teori hukum tata negara, ini disebut gagalnya kontrak sosial. Negara boleh menuntut loyalitas, tetapi loyalitas tidak bisa dipaksa jika keadilan tidak pernah hadir.
Korupsi pun lahir dari rahim yang sama. Ketika kewenangan dan anggaran menumpuk di pusat, pusat kekuasaan berubah menjadi pasar rente. Setiap izin menjadi komoditas, setiap kebijakan menjadi transaksi. Kita boleh menangkap ratusan koruptor, tetapi selama desain negara tetap sentralistik korupsi akan selalu menemukan jalannya. Ini tidak hanya persoalan moral, tetapi persoalan struktur kekuasaan.
Di titik inilah negara federal menjadi gagasan yang ditakuti. Tidak karena berbahaya bagi rakyat, namun karena berbahaya bagi elit pusat. Federalisme membatasi kekuasaan pusat secara konstitusional, memberi daerah kewenangan nyata dan memaksa pertanggungjawaban lebih dekat kepada rakyat. Dengan negara federal birokrasi dipangkas, kekuasaan dipecah, serta korupsi lebih sulit menjadi sistemik.
Pendapat Romo Y.B Mangunwijaya ini berangkat dari argumen Bung Hatta yang adalah seorang federalis. Bapak Proklamator ini tidak membayangkan Indonesia dikelola oleh satu pusat kekuasaan raksasa. Bagi Hatta, Indonesia yang majemuk, luas serta tersebar tidak mungkin adil jika dipaksa tunduk pada satu model sentralistik. Gagasan Indonesia Serikat jangan difahami pengkhianatan, melainkan alternatif rasional untuk mencegah dominasi pusat dan ketidakadilan daerah. Bahwa gagasan itu kemudian dikubur oleh kepentingan politik, bukan oleh argumen hukum. Sekali lagi ini adalah fakta sejarah yang jarang dibicarakan secara jujur.
Lalu datang bantahan klasik bahwa negara federal bertentangan dengan UUD 1945, ini keliru. Konstitusi bukan kitab suci, tapi adalah living constitution. Pasal 37 UUD 1945 secara tegas membuka ruang perubahan konstitusi, termasuk struktur ketatanegaraan, melalui mekanisme demokratis. Mengusulkan negara federal bukan tindakan inkonstitusional, melainkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sudah lama tergerus dan terwariskan oleh ketimpangan.
Bagaimana dengan “NKRI harga mati”? Secara hukum tata negara, slogan bukan norma. Norma harus diuji pada tujuan konstitusi yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika satu bentuk negara secara sistemik menghambat tujuan itu, maka mengoreksinya adalah kewajiban konstitusional, bukan pengkhianatan. Negara dipertahankan demi rakyat, bukan rakyat dikorbankan demi bentuk negara.
Ketakutan bahwa federalisme akan memecah Indonesia adalah kecacatan berpikir. Negara lebih sering pecah karena ketidakadilan yang dipertahankan, bukan karena kekuasaan yang dibagi. Yugoslavia runtuh karena dominasi pusat, bukan karena federalisme dan Romo Mangun telah lama memperingatkan agar Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama.
Negeri ini harus jujur pada dirinya sendiri. Terus mempertahankan negara kesatuan yang terbukti memproduksi ketimpangan, kemiskinan sekaligus korupsi bukanlah nasionalisme, melainkan penyangkalan kolektif. Negara federal bukan jaminan langsung yang secara spontan mengantarkan negara ini kepada kemakmuran, tetapi ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan republik dari kebohongannya sendiri. Jika itu dianggap ekstrem, mungkin karena kebenaran memang tidak pernah nyaman. Jika “NKRI harga mati” berarti ketimpangan harga mati, kemiskinan harga mati bahkan korupsi harga mati. Maka yang harus dipertahankan bukanlah bentuk negara, melainkan keberanian untuk mengubahnya.