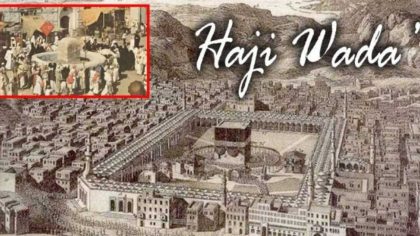(Cerpen Fiktif, Tapi Reflektif. Asu!)
Bukan pengalaman penulis.
Saya dulu tipe mahasiswa yang kata beberapa dosen bisa dibilang “hidup”. Sering angkat tangan, sering bertanya kadang sok pintar menjawab pertanyaan di kelas. Bukan karena paling tahu, tapi karena merasa kampus adalah tempat paling aman untuk berpikir keras. Toh katanya universitas adalah ruang kebebasan akademik. Tempat nalar diuji. Belakangan saya tahu, keyakinan itu terlalu polos.
Menjelang wisuda, kenyataan kecil sangat perih itu datang. Predikat kelulusan ternyata tidak selalu ramah pada mereka yang terlalu aktif berpikir. Ada yang jarang terlihat di kelas, tapi nilainya mulus dan rapi. Ada pula yang “rajin silaturahmi” ke Dosen, entah untuk urusan apa. Sementara yang terlalu sering bertanya, ya, dianggap “cukup baik”. Tidak buruk, tapi juga tidak perlu terlalu diapresiasi.
Di titik ini, saya teringat Louis Althusser. Althusser menyebut pendidikan sebagai aparatus ideologi negara. Artinya, sekolah dan kampus bukan hanya tempat transfer ilmu, tapi juga mesin halus untuk membentuk manusia yang patuh. Sistem tidak perlu melarang mahasiswa berpikir kritis. Cukup buat kekritisan itu tidak punya insentif!.
Kampus modern tampaknya sangat paham strategi ini. Mahasiswa boleh kritis, asal tahu waktu. Boleh bertanya, asal tidak mengganggu kenyamanan akademik.
Boleh menulis tajam, asal tidak terlalu keras. Sistem penilaian lalu bekerja sebagai penjinak seperti nilai, IPK, predikat cumlaude. Semua tampak objektif, transparan serta tentu saja sangat administratif.
Memang tidak ada pembungkaman, tapi ada pengkondisian. Lama-lama mahasiswa belajar sendiri seperti lebih aman diam, lebih strategis dekat dengan otoritas lebih menguntungkan mengikuti arus. Kekritisan pun direduksi menjadi lomba esai, seminar ataupun postingan “selamat” atas hari-hari besar, dosen mendapat gelar doktor ataupun prestasi satu/dua mahasiswa dengan caption media sosial rapi. Jujur, ini aman bahkan tidak mengganggu struktur sama sekali!.
Althusser pernah bilang, ideologi bekerja paling efektif justru saat kita tidak merasa sedang diideologisasi. Ketika ketidakadilan nilai dianggap urusan teknis.
Saat relasi kuasa dibungkus profesionalisme. Ketika sistem akademik dipahami sebagai sesuatu yang netral dan tak perlu terlalu sering dipertanyakan. Di situlah kampus berhasil melahirkan lulusan cerdas yang teramat jinak.
Tentu, tidak semua kampus demikian. Tidak semua dosen sama. Namun pengalaman kecil ini selama kuliah cukup untuk menunjukkan bahwa sistem pendidikan bisa sangat ramah pada kepatuhan dan cukup alergi pada kekritisan yang konsisten.
Barangkali itu adalah harga yang harus diri ini bayar. Atau mungkin, itu tanda bahwa kita perlu kembali bertanya tidak hanya di kelas, tapi pada sistem yang diam-diam mengajari kita kapan harus berhenti berpikir kritis.
Tahu kenyataan semacam itu, sudi lah terlalu aktif dulunya. Meski melakukannya pun tujuannya agar tidak menyesal. Tapi Asu!