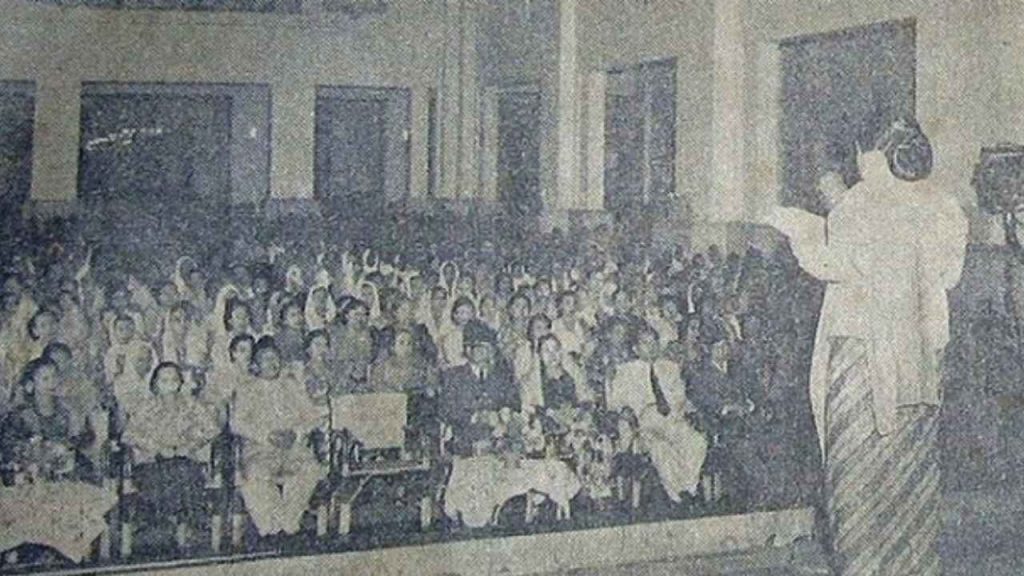Jakarta – Setelah malam 30 September 1965, Indonesia tenggelam dalam gelombang kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu hanya beberapa bulan, ratusan ribu orang dibunuh, jutaan lainnya ditahan tanpa pengadilan.
Tragedi ini, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), bukan ledakan spontan rakyat, melainkan operasi sistematis yang terorganisir.
Laporan penyelidikan Komnas HAM yang diselesaikan pada 2012 menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat terjadi “secara meluas dan terencana”, dengan pola yang sama di banyak wilayah Indonesia.
Dari Aceh sampai Nusa Tenggara, aparat militer bersama kelompok sipil melakukan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual dengan dalih “penumpasan komunis”.
Pola Kekerasan yang Sama di Seluruh Negeri
Berdasarkan temuan Komnas HAM, pola kekerasan berlangsung dalam tiga tahap besar:
- Penangkapan massal, dilakukan tanpa surat resmi, hanya berdasarkan tuduhan atau laporan aparat desa.
- Penyiksaan dan interogasi, untuk memaksa pengakuan keterlibatan dalam PKI atau organisasi yang diasosiasikan dengannya.
- Eksekusi tanpa pengadilan, dilakukan secara tertutup di hutan, sungai, hingga halaman kantor pemerintahan.
Di Jawa Tengah, penangkapan dilakukan oleh aparat Kodam Diponegoro, sementara di Jawa Timur dan Bali, operasi penumpasan melibatkan militer bersama ormas sipil seperti Ansor dan Banser.
Di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, pola serupa juga ditemukan: warga sipil digiring ke pos militer, lalu hilang tanpa jejak.
“Peristiwa pembunuhan berlangsung dengan pola yang identik dan jangka waktu yang berdekatan, menunjukkan adanya koordinasi komando dari pusat,” tulis Komnas HAM dalam laporannya.
Komnas HAM menemukan indikasi ribuan kuburan massal yang tersebar di berbagai daerah, banyak di antaranya tak pernah diidentifikasi. Warga di Blitar Selatan, Banyuwangi, Bali, dan Lampung melaporkan adanya lokasi-lokasi “keramat” tempat mayat-mayat korban dikuburkan bersama.
Para saksi menyebut bahwa korban sering kali dibunuh di malam hari dan dikubur terburu-buru. Di banyak kasus, keluarga bahkan tidak tahu di mana jasad kerabat mereka dimakamkan.
Salah satu penyintas di Jawa Timur mengisahkan, “Kami diminta menggali tanah, lalu disuruh menutup lubang yang berisi orang-orang yang baru saja ditembak. Tidak ada doa, tidak ada nama.”
Setelah gelombang pembunuhan pertama, operasi berlanjut dengan penahanan massal. Ratusan ribu orang ditahan tanpa proses hukum di penjara-penjara darurat, lapangan militer, hingga kamp isolasi di pulau-pulau terpencil.
Komnas HAM mencatat, penahanan ini dilakukan di luar sistem peradilan dan tanpa dasar hukum yang sah. Di banyak tempat, tahanan dipaksa bekerja membangun jalan, membuka lahan pertanian, atau bahkan membangun markas militer.
Pulau Buru menjadi simbol dari kekejaman sistem ini. Ribuan tahanan politik dikirim ke sana untuk kerja paksa di bawah pengawasan ketat tentara. Mereka hidup dalam kondisi minim makanan, tanpa perawatan medis, dan dengan ancaman kekerasan setiap hari.
“Kerja paksa menjadi bentuk lanjutan dari hukuman tanpa pengadilan,” kata laporan Komnas HAM. “Tahanan diperlakukan sebagai musuh negara, bukan warga negara.”
Di tengah kekacauan itu, ribuan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka dilecehkan, diperkosa, atau dipaksa menikah dengan aparat untuk menyelamatkan diri dari penahanan.
Sebagian besar tidak pernah melapor karena stigma sosial yang melekat kuat. Dalam banyak kasus, mereka justru disalahkan dan dijauhi oleh masyarakat.
“Kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari strategi penghinaan politik,” tulis Komnas HAM, “bukan sekadar tindak kekerasan seksual biasa.”
Hingga kini, negara belum pernah mengakui tanggung jawab atas kejahatan berbasis gender dalam tragedi 1965.
Salah satu temuan kunci Komnas HAM adalah keterlibatan langsung aparat negara dalam operasi kekerasan. Struktur komando militer, koordinasi antar-daerah, serta pola identik dalam penangkapan dan pembunuhan menunjukkan bahwa peristiwa 1965 bukanlah aksi balas dendam rakyat, melainkan tindakan terorganisir oleh negara.
Komnas HAM menyebut peristiwa ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, khususnya kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.
Namun, hingga laporan itu diserahkan ke Kejaksaan Agung, tidak ada satu pun langkah hukum yang diambil. Kasusnya mandek di meja penyidik, sementara korban terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang.
Tragedi 1965 meninggalkan lebih dari sekadar korban jiwa. Ia mewariskan ketakutan dan stigma yang menular lintas generasi. Banyak anak korban yang tumbuh dalam pengawasan aparat, kehilangan akses pendidikan, dan dicap “keluarga PKI” seumur hidupnya.
“Pelanggaran HAM berat ini bukan hanya peristiwa masa lalu,” tulis Komnas HAM, “tapi kejahatan yang akibatnya masih terasa hingga kini.”
Sumber: Dokumen Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966