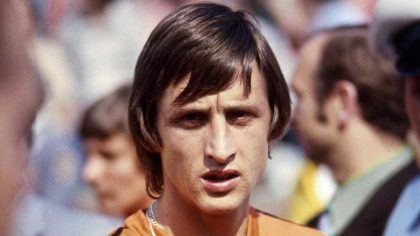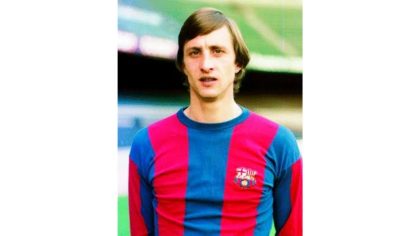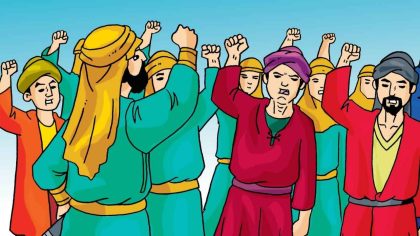Blitar – Di antara semak dan tebu, di tanah yang tak bertanda, ada keheningan yang lebih keras dari jeritan. Di tempat-tempat seperti inilah ribuan korban 1965 dikuburkan tanpa nama, tanpa nisan, tanpa doa.
Lebih dari setengah abad kemudian, para penyintas dan peneliti masih berusaha membuka tanah itu, bukan untuk membangkitkan mayat, tapi untuk memulihkan kemanusiaan.
Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut, pencarian kuburan massal adalah bentuk paling nyata dari perlawanan terhadap lupa. Ia menantang negara yang selama puluhan tahun menutup mata, sekaligus menyingkap bukti paling konkret bahwa pembunuhan itu memang pernah terjadi.
Sejak awal 2000-an, sejumlah lembaga masyarakat sipil mulai memetakan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat pembantaian massal. Hasilnya mengejutkan: lebih dari 3.000 titik di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Flores.
Sebagian besar berada di tepi sungai, kebun tebu, bekas pabrik gula, dan hutan jati lokasi yang tersembunyi tapi mudah dijangkau saat itu.
Di Jawa Timur, lokasi yang paling dikenal adalah Blitar Selatan, tempat ribuan orang dieksekusi oleh pasukan militer dan kelompok sipil.
Di Bali, titik pembantaian ditemukan di pinggir sungai Petanu, Gianyar, dan di ladang-ladang Bangli.Sementara di Sumatera Utara, peneliti menemukan kuburan massal di areal perkebunan lama milik perusahaan kolonial.
“Setiap kali kami menggali, kami tidak hanya menemukan tulang,” kata salah satu peneliti yang dikutip dalam laporan itu, “kami menemukan bukti bahwa negara berbohong.”
Pencarian kuburan massal tidak mudah. Banyak lokasi kini menjadi lahan warga, kompleks militer, bahkan kawasan wisata. Izin penggalian hampir selalu ditolak dengan alasan “tidak ada kepastian sejarah” atau “dapat menimbulkan keresahan masyarakat.”
Bahkan ketika warga setempat tahu dan bersedia membantu, mereka tetap takut. “Kalau ada aparat tahu kami gali, bisa-bisa dianggap mau menghidupkan PKI,” kata salah satu warga Wlingi yang diwawancarai tim Dalih Pembunuhan Massal.
Negara menolak menggali dengan alasan teknis, tapi sejatinya karena penggalian adalah bentuk pengakuan. Dan pengakuan berarti membuka kembali luka yang selama ini ditutup rapat oleh kekuasaan.
Meski tak semua bisa digali, banyak situs pembunuhan masih menyimpan tanda-tanda. Bekas gundukan tanah yang tak pernah ditanami, sumur tua yang ditutup batu, atau sungai yang mengalir dengan arah yang “dihindari warga.”
Di Kediri, warga masih menyebut satu area di tepi sungai sebagai “tempat orang hilang.” Di Bali, beberapa keluarga masih datang diam-diam setiap tahun, menaruh bunga tanpa menyebut nama siapa pun.
Di Sumatera, pekerja kebun yang menemukan tulang di bawah pohon sawit hanya menutupnya kembali dan berpura-pura tidak tahu. “Setiap jengkal tanah yang tak ditanami,” tulis laporan itu, “bisa jadi tempat negara menyembunyikan jenazahnya sendiri.”
Proyek penggalian yang dilakukan oleh tim forensik independen, termasuk dari Universitas Indonesia dan beberapa lembaga HAM, sempat menemukan sisa-sisa tulang manusia di beberapa lokasi.
Namun prosesnya selalu berhenti di tengah jalan karena tidak ada dukungan hukum. Padahal menurut standar internasional, penggalian semacam itu bukan tindakan.
Namun di Indonesia, menggali tulang masih dianggap tindakan subversif. “Kami ingin mengubur mereka dengan benar,” kata seorang penyintas. “Tapi negara bahkan takut pada orang mati.”
Pemerintah berkali-kali menolak inisiatif pencarian ini dengan alasan “belum ada keputusan resmi.” Padahal yang dicari bukan keputusan, melainkan pengakuan bahwa orang-orang itu pernah ada.
Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut ini sebagai politik penghapusan bukti. Selama lokasi-lokasi pembunuhan tidak diakui secara resmi, negara bisa terus berpura-pura bahwa kekerasan 1965 hanyalah “tragedi horizontal.”
“Diamnya negara bukan ketidaktahuan,” tulis laporan itu, “melainkan keputusan sadar untuk tidak tahu.”
Meski tanpa dukungan, para penyintas terus datang ke lokasi-lokasi itu setiap tahun. Mereka membawa bunga, dupa, lilin, kadang hanya air mata. Tak ada doa resmi, tak ada upacara kenegaraan, hanya ingatan yang keras kepala menolak dilenyapkan.
Di salah satu titik di Blitar Selatan, seorang perempuan tua berdiri di tepi sawah dan berbisik pada tanah: “Saya tidak tahu siapa yang di sini. Tapi saya tahu, mereka tidak salah.” Kalimat itu sederhana, tapi lebih kuat dari monumen mana pun.
Pencarian kuburan massal adalah upaya menemukan kebenaran yang paling dasar: bahwa sebelum negara bicara tentang ideologi, politik, atau rekonsiliasi, ia harus mengakui dulu bahwa ribuan tubuh dikuburkan tanpa nama. Selama tulang-tulang itu belum diberi tempat, keadilan tetap tidak punya alamat.
Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa