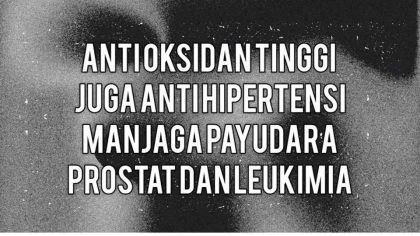Di sebuah sore yang basah oleh gerimis, saya duduk di depan basecamp Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) Bawana Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar. Aroma tanah dan kayu basah membaur dengan suara rintik hujan yang jatuh di atas terpal.
Sambil menyeruput kopi panas, pikiran saya melayang kepada sosok Soe Hok Gie, pemuda kurus berwajah tajam yang hidup dengan gelisah dan mencintai Indonesia dengan cara yang tidak biasa dengan mendaki gunung dan menulis perlawanan.
Gie bukan hanya seorang aktivis mahasiswa yang berani melawan ketidakadilan, ia juga pendaki yang menemukan kedamaian dalam sunyi gunung. Ia menulis dalam Catatan Seorang Demonstran, “Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal obyeknya”.
Dari kalimat itu saya belajar, bahwa mencintai Indonesia tidak cukup dilakukan dari balik meja kuliah atau layar ponsel. Kita harus menapaki tanahnya, mencium udaranya serta berbicara dengan rakyatnya, dan merasakan sakit yang mereka rasakan.
Sebagai anggota Mapala dan juga aktivis PMII di Rayon Ekonomi Komisariat Madjapahit Unisba Blitar, saya memilih untuk berjalan di jalur yang sama yakni, jalur sunyi penuh debu dan duri.
Jalur yang tidak selalu populer di kalangan mahasiswa masa kini yang sering lebih tergoda pada gaya hidup praktis, instan, dan hedonistik. Tapi saya percaya, seperti kata Gie, “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan”.
Di gunung, kami belajar tentang hidup. Tentang bagaimana kesederhanaan bisa mendekatkan manusia pada Tuhan. Tentang bagaimana persahabatan ditempa oleh rasa lapar dan dingin, bukan hanya oleh janji-janji manis.
Tapi lebih dari itu, kami belajar tentang Indonesia yang sesungguhnya yang tidak kita temukan dalam buku teori pembangunan ataupun dalam orasi-orasi birokrasi kampus.
Kami melihat langsung bagaimana desa-desa di kaki gunung kehilangan sumber air bersih karena hutan yang rusak, bagaimana masyarakat adat kehilangan hutan karena tambang legal yang dilindungi oleh kekuasaan, dan bagaimana anak-anak kecil bermain di sungai yang penuh limbah.
Sebagai mahasiswa pecinta alam, kami tidak tinggal diam. Di Mapala Bawana, kami mengadakan kegiatan konservasi, reboisasi, edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah, bahkan advokasi kecil-kecilan terhadap eksploitasi sumber daya alam di Blitar.
Di saat yang sama, sebagai kader PMII, saya dan kawan-kawan juga berdiskusi soal keadilan sosial, soal relasi antara negara dan rakyat serta soal keberpihakan mahasiswa dalam menghadapi kebijakan yang merugikan publik.
Bagi kami, mencintai alam dan memperjuangkan keadilan bukan dua hal yang terpisah. Keduanya satu tubuh, satu gerakan, satu napas. Sebab siapa yang paling menderita saat alam rusak? Rakyat kecil. Dan siapa yang paling sering dibungkam ketika bersuara? Mahasiswa.
Maka, menjadi Mapala yang sadar akan tanggung jawab sosial adalah panggilan zaman. Kita tidak boleh hanya mendaki demi kesenangan, berfoto demi eksistensi, atau mencintai alam tanpa mengerti penderitaan manusia yang tinggal di sekitarnya.
Kadang, saya bertanya dalam hati, masih adakah tempat bagi idealisme di tengah kampus hari ini? Ketika organisasi-organisasi mulai dipenuhi kepentingan pribadi dan gerakan mahasiswa terasa hambar, kehilangan arah, hanya menjadi formalitas.
Tapi saya teringat Gie, yang dalam keterasingannya tetap menulis, tetap mendaki, tetap berjuang. Ia tahu dunia tidak akan berubah seketika, tapi ia juga tahu bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani.
Hari ini di Unisba Blitar, saya dan beberapa mahasiswa lain mencoba melanjutkan warisan itu. Kami mungkin belum sehebat Gie, belum seberani ia dalam mengkritik penguasa, tapi kami berusaha untuk jujur.
Kami ingin Mapala bukan hanya tempat naik gunung, tapi juga tempat menempa keberanian dan kepedulian. Kami ingin PMII bukan hanya tempat diskusi, tapi juga ruang pembentukan moral dan nurani yang hidup.
Kami percaya, gunung bukan hanya tempat tinggi, tapi juga tempat untuk menemukan makna hidup. Dan organisasi bukan hanya tempat berproses, tapi tempat memutuskan akan menjadi manusia macam apa kita ke depan. Di tenda-tenda kecil saat ekspedisi, kami berbicara tentang negeri ini, tentang harapan, dan tentang cita-cita menjadi manusia yang berguna.
Gie telah pergi di puncak Semeru tahun 1969, tapi nilai-nilainya masih hidup di hati kami. Ia mengajarkan bahwa mahasiswa sejati adalah mereka yang berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang tahu kapan harus melawan, kapan harus diam, dan kapan harus turun tangan membantu sesama.
Kami mahasiswa Unisba Blitar, anak-anak Mapala dan PMII, akan terus berjalan, meski pelan, meski tertatih. Karena kami tahu, jalan ini adalah jalan panjang menuju kemerdekaan jiwa. Dan seperti yang Gie katakan, “Hidup adalah soal keberanian. Keberanian untuk menanggung resiko. Keberanian untuk melawan. Dan keberanian untuk tetap setia pada suara hati”.