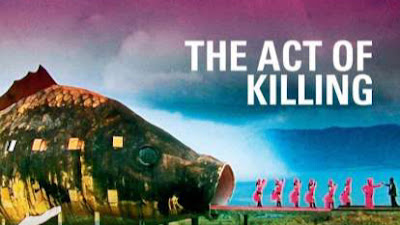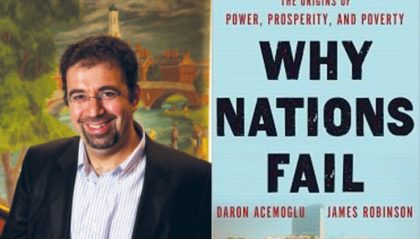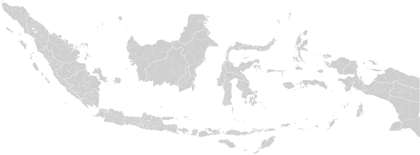Jakarta – Selama lebih dari lima dekade, negara menunda satu hal yang seharusnya paling sederhana: mengakui bahwa pembunuhan massal 1965 adalah kejahatan negara.
Bukan kekacauan rakyat, bukan perang ideologi, tapi kebijakan yang dijalankan dengan struktur, perintah, dan impunitas.
Laporan Dalih Pembunuhan Massal menulis tanpa tedeng aling-aling: “Negara tidak hanya gagal melindungi warganya, tapi secara aktif mengatur pembunuhan mereka.” Namun, meski bukti dan saksi berserakan, perjuangan hukum para korban berjalan seperti berlari di tempat.
Sejak reformasi 1998, berbagai lembaga telah berulang kali menjanjikan penyelesaian. Komnas HAM menyelesaikan laporan penyelidikan pro-justisia pada 2012 yang menyatakan bahwa peristiwa 1965 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tapi Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti. Alasan resminya: tidak cukup bukti, sulit menentukan pelaku, dan kasus terlalu lama. Alasan sesungguhnya: pelakunya adalah negara itu sendiri.
Komnas HAM mengajukan ulang berkas pada 2016 dan 2020, namun hasilnya sama. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bahkan sempat menyebut bahwa penyelesaian “lebih baik dilakukan secara non-yudisial,” seolah pembunuhan massal bisa diselesaikan dengan upacara maaf-maafan. “Negara ingin menutup luka tanpa melihat darahnya,” tulis laporan tersebut.
Beberapa kali, pemerintah membentuk tim rekonsiliasi. Pada 2015, Presiden Joko Widodo menjanjikan “penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.” Tapi dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan bukan hukum, melainkan politik citra. Yang diundang hanya sebagian korban, tanpa mekanisme pengadilan, tanpa pelaku yang dimintai pertanggungjawaban.
Yang diberikan hanyalah pernyataan empati, bukan keadilan. Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut, rekonsiliasi tanpa pengakuan hanyalah ritual administratif untuk menenangkan opini internasional. “Negara ingin disebut beradab, tapi tidak berani bertatap muka dengan korban.”
Upaya di Forum Internasional
Karena hukum nasional tertutup, para penyintas dan aktivis HAM mulai membawa kasus ini ke dunia internasional. Pada 2015, digelar International People’s Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag, Belanda.
Tribunal ini bukan pengadilan resmi PBB, tapi forum moral yang menghadirkan puluhan saksi dan ahli hukum dari berbagai negara. Hasilnya jelas: panel hakim menyatakan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa 1965–1966.
Tapi pemerintah Indonesia menolak hasil itu dengan alasan “tidak mengikat secara hukum.” Penolakan ini mempertegas satu hal: negara hanya tunduk pada hukum ketika hukum tidak menyentuhnya.
Selain jalur hukum, perjuangan korban juga berlangsung di ranah politik. Sejumlah anggota DPR pernah mengusulkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tapi RUU-nya dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006 karena dianggap memberi ruang impunitas bagi pelaku.
Sejak saat itu, tak ada payung hukum baru yang bisa menampung penyelesaian kasus 1965. Negara bersembunyi di balik ketiadaan mekanisme, menjadikan ketidakmampuan sebagai strategi.
“Tidak ada hukum yang menghalangi keadilan,” tulis laporan itu, “kecuali kehendak politik untuk tidak menegakkannya.”
Meski diabaikan, para penyintas terus melawan. Mereka menggugat lewat petisi, testimoni, film dokumenter, dan forum publik. Beberapa bahkan mendatangi istana, membawa foto orang tua mereka yang hilang.
“Kami tidak ingin uang, hanya ingin nama mereka diakui,” kata seorang penyintas dari Solo dalam kutipan laporan itu.
Gerakan mereka kecil, tapi konsisten. Mereka tahu bahwa negara tidak akan tiba-tiba berubah, tapi mereka juga tahu bahwa diam berarti ikut bersekongkol.
Sampai hari ini, tidak ada satu pun pejabat militer, aparat, atau pejabat sipil yang diadili atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan massal 1965. Sebaliknya, banyak dari mereka justru mendapat bintang jasa, kursi jabatan, dan nama jalan.
Laporan Dalih Pembunuhan Massal menulis dingin: “Di Indonesia, pembunuh bisa dimakamkan sebagai pahlawan, sementara korban tetap dikubur dua kali di tanah dan di sejarah.”
Bagi para korban, perjuangan hukum kini bergeser menjadi perjuangan ingatan. Jika negara menolak mengadili, maka sejarahlah yang akan melakukannya. Mereka menggelar pameran, membuat arsip digital, dan menulis buku.
Setiap testimoni baru adalah dakwaan yang tak bisa disangkal, setiap lokasi kuburan yang ditemukan adalah bukti yang tak bisa dihapus. “Kami tahu kami akan mati tanpa keadilan,” tulis seorang penyintas di akhir laporannya. “Tapi kami tidak akan mati tanpa meninggalkan kebenaran.”
Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa