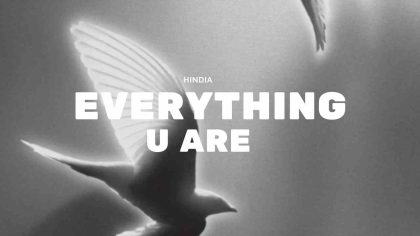Jakarta – Enam puluh tahun lalu, Indonesia memasuki bab paling kelam dalam sejarahnya. Peristiwa yang bermula pada malam 30 September 1965 bukan hanya mengguncang politik nasional, tapi juga mengubah arah kehidupan jutaan warga sipil.
Dari pusat kekuasaan di Jakarta hingga desa terpencil di pelosok Nusantara, bara kekerasan menyebar tanpa ampun.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan penyelidikannya menyebut tragedi 1965–1966 sebagai pelanggaran HAM berat yang terencana dan sistematis. Negara dinilai terlibat aktif dalam pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, serta penghilangan orang secara paksa.
Namun untuk memahami kedahsyatan tragedi ini, perlu menengok ke masa sebelum api itu menyala.
Ketegangan yang Mendidih
Awal 1960-an, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno dengan sistem politik “Demokrasi Terpimpin.” Negara dikuasai tiga kekuatan besar: militer, nasionalis, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kala itu menjadi partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok.
Di tengah situasi ekonomi yang memburuk, ketegangan antara militer dan PKI makin tajam. PKI secara terbuka mengkritik dominasi Angkatan Darat dan mendukung gagasan pembentukan “Angkatan Kelima” pasukan bersenjata rakyat yang dipersenjatai pemerintah. Gagasan itu dianggap mengancam posisi militer.
Komnas HAM mencatat bahwa menjelang September 1965, ketegangan politik sudah mendekati titik didih. Konflik ideologis, perebutan pengaruh, dan krisis ekonomi menjadi bahan bakar di bawah bara nasionalisme dan kecurigaan.
Tanggal 30 September 1965 malam, enam jenderal dan satu perwira menengah Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September (G30S).
Dalam hitungan jam, peristiwa itu direspons oleh Mayjen Soeharto, yang segera mengambil alih komando Angkatan Darat dan menuding PKI sebagai dalang.
Keesokan harinya, narasi tunggal langsung dibangun: G30S disebut sebagai kudeta PKI. Radio, surat kabar, dan pengeras suara di masjid-masjid menyiarkan propaganda anti-komunis yang membakar kemarahan publik. Dalam waktu singkat, kekerasan meluas ke berbagai daerah.
“Tidak ada proses hukum. Hanya daftar nama dan perintah untuk menumpas,” tulis Komnas HAM dalam ringkasan laporannya.
Pembunuhan massal dimulai pada Oktober 1965. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, ribuan orang dieksekusi tanpa pengadilan. Sebagian besar bahkan tidak tahu mengapa mereka ditangkap.
Tentara, aparat desa, dan kelompok sipil pro-militer bekerja bahu-membahu dalam operasi penumpasan. Komnas HAM menemukan pola yang sama di hampir semua daerah: warga dikumpulkan di balai desa, diinterogasi, lalu dibawa pergi — sebagian besar tak pernah kembali.
“Peristiwa 1965 bukan reaksi spontan rakyat,” tulis laporan itu. “Ada perencanaan dan koordinasi yang menunjukkan keterlibatan langsung aparat negara.”
Setelah pembunuhan besar-besaran, gelombang kedua kekerasan terjadi: penahanan dan pembuangan massal. Puluhan ribu orang dikirim ke kamp tahanan di Pulau Buru, Nusakambangan, dan berbagai lokasi lain tanpa proses hukum.
Di tempat-tempat itu, mereka dijadikan tenaga kerja paksa selama bertahun-tahun.
Pemerintah Orde Baru yang berdiri setelah 1966 menggunakan tragedi ini sebagai dasar legitimasi kekuasaan selama lebih dari tiga dekade. Setiap bentuk kritik terhadap narasi resmi dianggap subversif.
Bagi korban, 1965 bukan hanya soal kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan identitas. Mereka yang selamat harus hidup dalam stigma sebagai “eks-tapol” tahanan politik dan diawasi hingga puluhan tahun kemudian.
Warisan Ketakutan
Komnas HAM menegaskan, peristiwa 1965 bukan sekadar konflik ideologi, tapi pelanggaran HAM berat dengan korban yang sangat luas. Luka sosialnya masih terasa hingga kini: diskriminasi terhadap keluarga korban, pelarangan kegiatan sosial, dan penghapusan sejarah alternatif di ruang publik.
Bagi bangsa ini, tragedi 1965 adalah peringatan pahit tentang betapa mudahnya kekuasaan mengubah ketakutan menjadi alat pembenaran.
Enam dekade kemudian, sejarah itu masih menunggu keberanian negara untuk menatapnya jujur, bukan sebagai catatan lama, tapi sebagai tanggung jawab yang belum selesai.
Sumber: Dokumen Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966