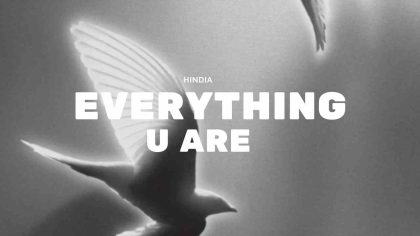Jakarta – Hampir enam puluh tahun setelah tragedi 1965, negara masih bungkam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengadilan, dan tidak ada pemulihan yang layak bagi para korban.
Tapi di tengah sunyi itu, segelintir orang tetap bergerak. Mereka adalah para penyintas, keluarga korban, dan organisasi masyarakat sipil yang menolak menyerah pada lupa.
Salah satu kekuatan utama dalam gerakan ini adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Sejak 1998, lembaga ini aktif mendorong negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965.
Bersama berbagai jaringan, mereka mengumpulkan data, mengadvokasi kebijakan, dan membuka ruang bagi korban untuk bersuara.
“Negara boleh diam, tapi ingatan tidak bisa dibungkam,” kata salah satu aktivis KontraS dalam laporan Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965.
Menagih Janji Komnas HAM
Langkah paling konkret dari masyarakat sipil adalah mendorong Komnas HAM agar melakukan penyelidikan pro justisia, penyelidikan dengan tujuan hukum, atas peristiwa 1965–1966.
Desakan itu akhirnya membuahkan hasil pada 2012, ketika Komnas HAM merampungkan laporan setebal hampir seribu halaman yang menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat.
Namun laporan itu berhenti di meja Kejaksaan Agung. Hingga kini, tidak ada proses hukum yang berjalan. Negara memilih diam, sementara para korban semakin menua.
“Keadilan itu seperti janji kosong yang terus diulang,” ujar salah satu penyintas di Blitar Selatan kepada tim KontraS.
Selain mendesak penegakan hukum, organisasi masyarakat sipil juga menyoroti keberadaan berbagai aturan diskriminatif warisan Orde Baru yang masih berlaku.
Misalnya, Keputusan Presiden No. 28/1975 tentang perlakuan terhadap “terlibat G30S” yang membagi warga dalam kategori A, B, dan C. Aturan ini menjadi dasar bagi pelabelan “eks-tapol” di KTP dan penolakan terhadap hak-hak sipil korban.
Upaya pencabutan aturan-aturan semacam itu terus dilakukan, meski hasilnya lambat. Beberapa peraturan sudah tak berlaku secara praktik, tapi tak pernah resmi dicabut. Bagi korban, itu berarti stigma masih menempel secara hukum.
“Kalau negara serius bicara rekonsiliasi, langkah pertama adalah mencabut semua dasar hukum yang menindas korban,” tegas laporan KontraS.
Di beberapa daerah, pemerintah daerah sempat menjanjikan program rehabilitasi sosial bagi korban 1965. Tapi janji itu tak pernah berjalan konsisten. Banyak penyintas bahkan tak tahu mereka punya hak atas pemulihan.
Program seperti pemberian bantuan kesehatan dan kesejahteraan berhenti di atas kertas. Korban yang masih hidup seringkali hidup miskin, sakit, dan terisolasi. “Kami tidak butuh belas kasihan,” kata seorang korban di Buton. “Kami hanya ingin nama kami dibersihkan.”
Membangun Ingatan, Bukan Sekadar Arsip
Karena negara enggan membuka kebenaran, masyarakat sipil beralih pada cara lain: pendokumentasian independen.
KontraS dan jaringan seperti Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) membuat sistem pendataan digital untuk menyimpan kesaksian, dokumen, dan bukti pelanggaran.
Sistem ini bukan sekadar arsip, tapi senjata melawan pelupaan. Melalui data, mereka memastikan kisah para korban tetap hidup dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya, sebuah bentuk keadilan simbolik yang lahir dari masyarakat, bukan negara.
Satu per satu korban mulai berpulang, membawa cerita yang belum sempat didengar. Waktu menjadi musuh utama bagi perjuangan keadilan. Tapi selama ada yang mau mencatat, berbicara, dan menuntut, kisah itu tak akan hilang.
“Negara mungkin menunda, tapi sejarah tak akan lupa siapa yang diam,” tulis penutup laporan KontraS.
Sumber: KontraS – Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian