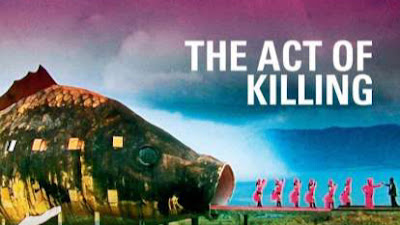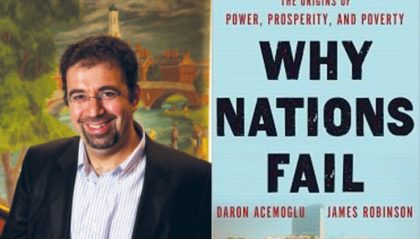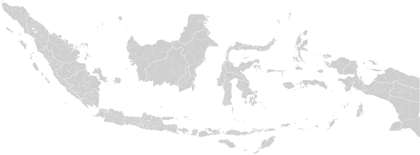Blitar – Setiap bangsa punya kisah tentang bagaimana mereka merumuskan masa depannya. Bagi negeri ini momen itu terjadi pada tahun 1945, ketika para pendiri bangsa duduk bersama dalam sebuah forum BPUPK (Badan Persiapan Usaha – Usaha Kemerdekaan) atau istilah penjajahnya Dokuritsu Junbi Cosakai.
Di sanalah untuk pertama kalinya, bangsa ini secara serius membicarakan tentang negara merdeka yang sebentar lagi lahir akan berbentuk apa?.
Pertanyaan sederhana ini ternyata memunculkan perdebatan panjang yakni apakah Indonesia harus melanjutkan tradisi kerajaan yang akrab di benak rakyat, atau memilih bentuk republik yang dianggap modern dan demokratis?.
Perdebatan tersebut bukan sekadar adu gagasan, tetapi juga cermin dari kegelisahan bangsa baru dengan harapan bangkit dari penjajahan. Bagi sebagian orang, kerajaan terasa lebih dekat dengan tradisi Nusantara. Namun, bagi tokoh lain, republik adalah simbol kebebasan dan kedaulatan rakyat.
Ketegangan inilah yang akhirnya mewarnai sidang-sidang BPUPK (penulis lebih nyaman memakai singkatan ini daripada BPUPKI), hingga diputuskan melalui voting. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa negara ini lahir dari sebuah persimpangan jalan sejarah.
Sejarah Indonesia modern merekam momen krusial di tahun 1945, ketika para pendiri bangsa bersidang dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Selain membicarakan dasar negara forum ini juga memperdebatkan bentuk negara, apakah Indonesia merdeka kelak akan menjadi kerajaan atau republik. Risalah sidang BPUPK memperlihatkan dinamika tajam yang akhirnya diselesaikan lewat pemungutan suara.
Awal gagasan republik muncul pada 29 Mei 1945, di Gedung Chuo Sangi-In, Jakarta (kini Gedung Pancasila). Dalam pidatonya, Muhammad Yamin memaparkan “Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”.
Ia menegaskan bahwa republik adalah bentuk yang paling sesuai dengan semangat nasionalisme modern, unitarisme, dan kedaulatan rakyat. Yamin menolak bentuk monarki karena dianggap berlawanan dengan cita-cita demokrasi.
Perdebatan semakin tajam pada 10 Juli 1945, ketika BPUPK bersidang di Gedung Pejambon, Jakarta. Di forum ini, Soesanto Tirtoprodjo menyampaikan pandangan bahwa rakyat Indonesia lebih mengenal kerajaan. Ia menyebut, “rakyat jelata lebih akrab dengan bentuk kerajaan,” meski sadar bahwa sulit mencari figur raja yang bisa diterima semua pihak.
Sebagai jalan tengah, ia mengusulkan kepala negara dipilih untuk jangka waktu tertentu tidak disebut presiden, tetapi membuka kemungkinan dinobatkan sebagai raja di kemudian hari.
Setelah itu anggota yang lain, P.F. Dahler menegaskan bahwa kemerdekaan lebih penting ketimbang memperdebatkan bentuk negara. Ia menilai republik atau kerajaan hanyalah bentuk luar, sedangkan substansinya adalah segera merdeka.
Dahler bahkan menyatakan tidak keberatan dengan republik, tetapi tetap terbuka pada kemungkinan monarki. Pandangannya mencerminkan sikap moderat dan pragmatis di tengah suasana politik yang mendesak.
Di sisi lain, M. Yamin tampil kembali dengan sikap tegas. Baginya, republik adalah simbol pembaruan dan kedaulatan rakyat. Ia menolak monarki karena dianggap feodal dan tidak relevan dengan cita-cita pergerakan nasional.
“Negara Republik Indonesia ialah suatu negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat penuh,” tegas Yamin.
Perdebatan terus berlanjut hingga 11 Juli 1945, ketika suasana sidang semakin panas. Untuk mengakhiri kebuntuan, Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat memutuskan agar dilakukan pemungutan suara tertulis. Dari 64 suara anggota yang hadir, hasilnya: 55 memilih Republik, 6 memilih Kerajaan, 2 memilih bentuk lain, dan 1 suara blanko.
Meski republik ditetapkan, dalam risalah sidang menunjukkan bahwa keputusan itu lebih didorong oleh semangat zaman dan kebutuhan praktis ketimbang argumen filosofis yang matang. Republik lahir di Indonesia lebih sebagai pilihan konsensus, taken for granted bukan hasil diskursus mendalam tentang arti res publica.
Terus terang, kegagapan ini masih terasa hingga hari ini. Republik jarang dibicarakan dalam ruang publik sebagai sistem nilai, melainkan hanya sebagai label formal negara. Akademisi seperti Dr. Robertus Robert pernah mengatakan, bagaimana kita bisa memahami etika publik atau etika politik, jika makna republik itu sendiri tidak pernah benar-benar dipahami?
Pertanyaan itu menohok, sebab problem etika politik Indonesia modern seperti korupsi, oligarki, lemahnya akuntabilitas tak bisa dilepaskan dari absennya pemahaman mendasar tentang arti republik.
Republik ini telah lama berdiri, namun tanpa fondasi konseptual yang kokoh. Delapan puluh tahun kemudian, republik tetap bertahan tetapi terus bergulat dengan makna dan konsekuensinya.
Sejarah tersebut mengajarkan kita bahwa republik harus dipahami bukan sekadar sebagai bentuk negara, melainkan sebagai res publica atau ruang bersama untuk mengabdi pada kepentingan umum. Mungkin sekarang telah sampai pada waktunya untuk mulai membahas tentang diskursus bentuk negara.